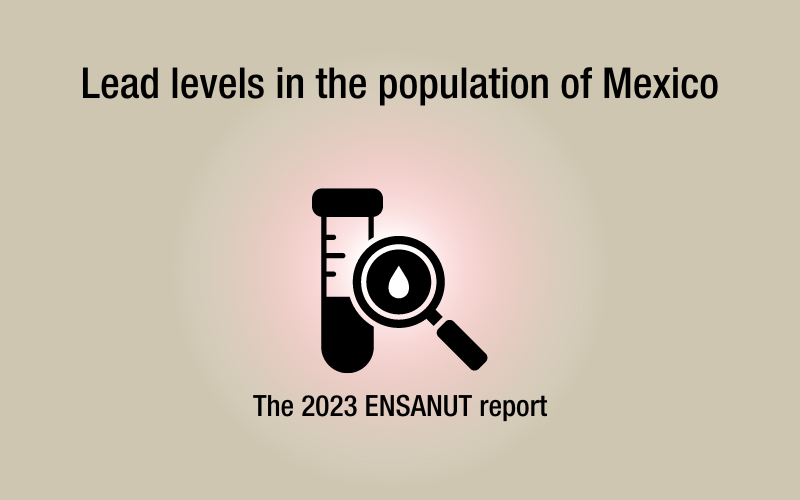Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Indonesia, Hendricus Andy Simarmata, menilai bahwa selama ini ada dikotomi antara aktivitas lingkungan dan ekonomi. Pemulihan lingkungan cenderung dilihat sebagai sebuah beban finansial. Hal ini salah satunya disebabkan karena banyak kebijakan dan intervensi di bidang perkotaan cenderung reaktif atau bertindak hanya setelah masalah muncul, yang justru membutuhkan biaya yang besar. Padahal dengan upaya antisipatif dan transformatif yang lebih strategis dan berbasis data, pemulihan lingkungan bisa menjadi sebuah investasi ekonomi. Bukti nyata dari inisiatif pemulihan lingkungan yang sukses bisa menjadi solusi untuk mengubah pola pikir reaktif tersebut.

“Pada perencanaan wilayah dan kota sekarang, mempertimbangkan aspek lingkungan harusnya bukan lagi hanya sebagai pelengkap tapi justru awal atau genesis dari perencanaan,” tegas Hendricus Andy Simarmata, ahli perencanaan kota dan akademisi yang selama 20 tahun terakhir berkontribusi dalam bidang tata kota dan pengelolaan lingkungan perkotaan baik di tingkat nasional maupun internasional.
Keyakinan Andy terhadap pentingnya aspek lingkungan pada perencanaan tata kota ini mulai terbentuk di awal kariernya. Andy terdorong untuk menempuh pendidikan pascasarjana dengan fokus pada pengembangan perkotaan setelah melihat banyaknya masalah lingkungan pada kota-kota di Indonesia. “Passion saya pada lingkungan semakin besar ketika menyusun tesis tentang adaptasi masyarakat terhadap pencemaran debu batubara di Banjarmasin,” kenang Andy.
Tesis yang ia susun pada 2006 tersebut menemukan korelasi positif antara pencemaran debu dan sejumlah masalah kesehatan yang dialami oleh para penduduk yang tinggal berdekatan dengan lokasi stockpile. Andy melihat bagaimana lingkungan yang baik akan memberikan kesehatan yang baik pula pada masyarakatnya, begitu pula sebaliknya dan bagaimana perencanaan tata ruang berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang baik ini.
Kini, hampir dua dekade setelahnya, di berbagai organisasi dan profesi yang ia jalani, baik sebagai ahli perencanaan kota, penasihat dan pendiri firma perencana, akademisi, maupun advokat, Andy, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) sejak 2019, terus mendorong pentingnya memasukkan aspek lingkungan pada penyusunan perencanaan tata ruang kota, bahkan sebagai layer pertama sebelum merencanakan kepentingan sosial dan ekonomi.
Berdasarkan pengamatan Andy, isu lingkungan kerap belum menjadi pusat perhatian dari praktik perencanaan tata ruang kota di Indonesia. Selain menyebabkan permasalahan lingkungan di kemudian hari, hal ini juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.
Beranjak dari reaktif menuju antisipatif
Menurut Andy, banyak kebijakan dan intervensi di bidang perkotaan cenderung reaktif atau bertindak hanya setelah masalah muncul. Salah satu contoh nyata adalah bagaimana pencemaran lingkungan sering kali baru ditangani setelah muncul dampak kesehatan yang signifikan pada masyarakat. “Masyarakat cenderung tidak peduli masalah limbah B3 (bahan berbahaya beracun). Mereka baru akan peduli ketika sudah ada yang terdampak masalah dari paparan timbal misalnya. Padahal, semestinya kita jangan begitu, alih-alih reaktif kita harus antisipatif.”
Andy berpendapat bahwa dengan perencanaan yang lebih strategis dan berbasis data, banyak masalah lingkungan dapat dicegah sejak dini. Ia mencontohkan, “Misalnya, untuk mengantisipasi berkembangnya industri EV (electric vehicle) atau kendaraan listrik, kita harus menghitung perkiraan jumlah baterai bekas dalam lima tahun ke depan. Perkiraan ini lah yang akan kita gunakan untuk membuat strategic paper terkait pengelolaan limbahnya.”

Lebih lanjut, Andy menyebut bahwa upaya antisipatif berupa penerapan environmental safeguard ini bisa menghindarkan sebuah wilayah atau kota dari kerugian ekonomi akibat pencemaran lingkungan. “Aktivitas ekonomi tanpa adanya environmental safeguard yang baik bisa menimbulkan kerugian ekonomi yang bahkan jauh lebih besar daripada investasi ekonomi itu sendiri.”
Andy berkaca pada pengalamannya terlibat dalam studi kelayakan dan penyusunan rencana pengembangan Desa Pesaren, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah untuk bertransformasi pasca pemulihan. Selama puluhan tahun, usaha peleburan logam dari limbah aluminium dan aki bekas skala rumahan menjadi mata pencaharian yang menjanjikan di Desa Pesarean. Meski mendongkrak perekonomian masyarakat, aktivitas ekonomi yang dilakukan tanpa standar keamanan dan kesehatan menghasilkan cemaran limbah B3 skala besar, khususnya timbal. Upaya pemulihan lingkungan akibat dari pencemaran ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ditambah lagi environmental health cost yang harus ditanggung oleh masyarakat di desa tersebut.
Upaya transformatif dalam pemulihan lingkungan
Pola reaktif, menurut Andy, juga terjadi pada upaya pemulihan lingkungan. Andy menilai bahwa banyak upaya penanganan pencemaran lingkungan hanya berhenti pada solusi jangka pendek. Misalnya, penggunaan modifikasi cuaca sebagai solusi polusi udara, yang selain mahal juga tidak menyelesaikan masalah dalam jangka panjang.
Alih-alih intervensi yang reaktif, Andy menekankan pentingnya membingkai ulang masalah dan tantangan yang ada untuk menghasilkan solusi jangka panjang yang tidak hanya efektif, tetapi juga transformatif. Upaya transformatif ini membutuhkan pelibatan dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait.
Dalam kasus Pesarean, misalnya, Andy menceritakan bagaimana upaya pemulihan lingkungan tidak hanya berhenti pada relokasi dan remediasi saja. Ada upaya pasca pemulihan yang bertujuan mentransformasi Desa Pesarean menjadi desa destinasi wisata dengan memanfaatkan aset budaya setempat, yakni makam Amangkurat I. Berbagai pemangku kepentingan, termasuk beberapa dinas terkait terlibat dalam rencana ini. Beberapa program ruang baru direncanakan di sekitar kawasan makam, sehingga nantinya pengunjung tidak hanya datang untuk berziarah tapi juga kegiatan wisata lainnya yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

“Kita perlu mencari cara bagaimana menciptakan added value dari kawasan tersebut. Sehingga pemulihan lingkungan, rehabilitasi lahan, dan pemulihan ekosistem bisa menjadi investasi ekonomi. Selama ini pemerintah, pengusaha, dan para pemangku kepentingan lain cenderung melihat pemulihan lingkungan sebagai cost.”
Tantangan terbesarnya, menurut Andy, tentu saja adalah mengubah pola pikir tersebut. “Tapi untuk mengubah mindset ini kita perlu bukti. Kita harus memperbanyak bukti bahwa betul kesejahteraan masyarakat akan jauh lebih meningkat jika lingkungannya diperbaiki dan dijaga,” jelasnya.
Lebih lanjut Andy menilai bahwa bukti berupa data, angka meningkatnya pendapatan masyarakat misalnya, akan jauh lebih kuat untuk meyakinkan masyarakat dan pemangku kepentingan tentang bagaimana pemulihan lingkungan bisa menjadi investasi. “Saya pikir kita perlu menunjukkan inisiatif-inisiatif atau kasus-kasus sukses untuk mengkomunikasikan hal tersebut.”
Baca juga: Breaking the Cycle of Extreme Lead Poisoning in Pesarean, Indonesia
Tiga bekal untuk misi bertransformasi
Andy berpendapat pemerintah memiliki peran yang penting untuk mendorong inisiatif pemulihan lingkungan yang transformatif. Ia menyebut tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menjalankan misi ini.
Yang pertama, mengembangkan model-model pemulihan lingkungan yang feasible secara ekonomi dengan mekanisme tanggung renteng. Pemerintah perlu menggandeng pemain industri atau pengusaha terkait untuk ikut terlibat, karena pemulihan lingkungan juga menjadi tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, adanya model ekonomi yang jelas menjadi hal yang penting.
“Jika kita membungkus masalah ini hanya sebagai masalah lingkungan, mereka akan menganggap ini masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan para aktivis saja,” jelasnya. Dalam hal ini, pemerintah bisa menggunakan APBD sebagai dana awal untuk menginisiasi para pengusaha, pemilik lahan, dan juga masyarakat sekitar untuk terlibat.
Kedua adalah mengembangkan teknologi pengelolaan lingkungan yang mumpuni. Menurut Andy, bergantung pada teknologi luar negeri membutuhkan biaya yang mahal. Oleh karena itu, pengembangan teknologi lokal bisa menjadi solusi. “Kita harus membangun R&D (research and development) dengan melibatkan kampus-kampus lokal. Mereka, terutama yang berkecimpung di bidang lingkungan, harus dilibatkan dalam riset-riset praktis.”

Ketiga adalah membuat peraturan perundangan yang mendukung. Jika ada industri baru yang belum diatur pada PP Penanganan Limbah B3, misalnya, maka perlu segera dibuatkan peraturannya. “Harus ada kontrol pengawasan terhadap itu. Governance adalah kunci, sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita terlambat dari market. Justru peraturan harus diubah untuk merespon market, supaya market bekerja sempurna.”
Mewujudkan kota berkelanjutan
Menurut Andy, pemerintah perlu memiliki sensitivitas dalam mengantisipasi dinamika yang ada untuk melakukan intervensi yang tepat. “Kota itu dinamis dan terus berkembang. Dinamika ini yang harus bisa diakomodasi oleh ruang. Jika berubah fungsi, misalnya, tidak akan terjadi masalah dan tetap berkelanjutan. Kota yang berkelanjutan memiliki aktivitas ekonomi yang produktif dan kompetitif tanpa adanya kelompok masyarakat yang termarjinalisasi dan tanpa merusak lingkungan. Memanusiakan kota (humanizing city), mengembangkan kemampuan adaptasi kota terhadap perubahan ekonomi (adapting city), dan memastikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan (sustaining urban ecosystem) adalah kunci kota keberlanjutan. Setiap perubahan pasti akan terjadi, yang penting kita bisa mengelola.”
Sehingga upaya antisipatif terhadap dinamika kota—termasuk bertambahnya jumlah dan kebutuhan penduduk, perubahan iklim, perkembangan teknologi dan industri baru, serta upaya transformatif terhadap permasalahan lingkungan yang ada, adalah komponen yang penting untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan.